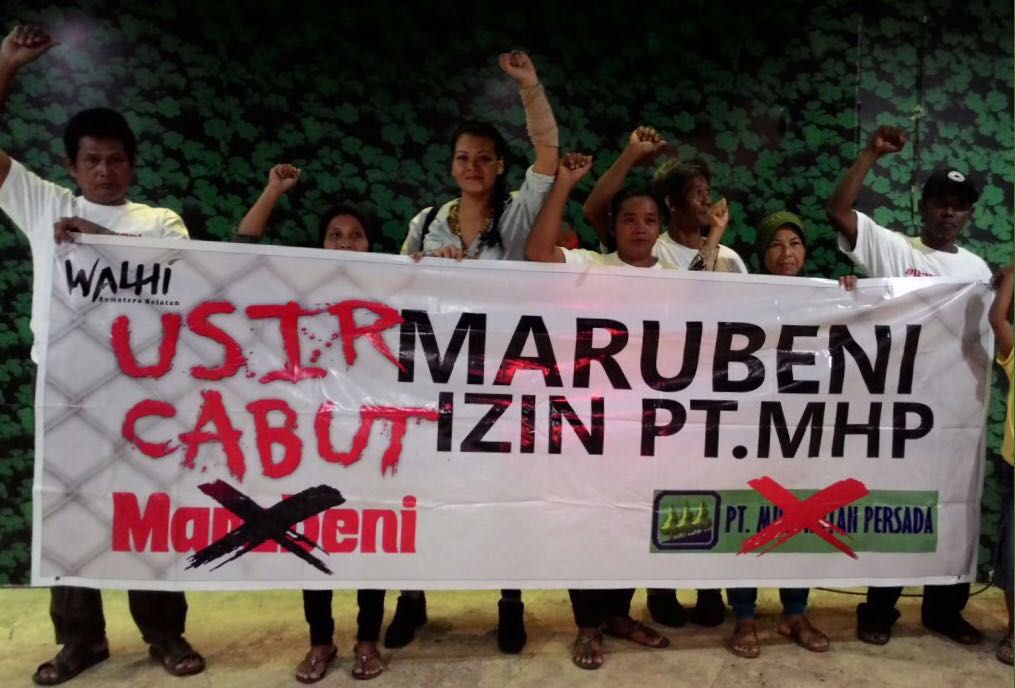Kadiv Hutan dan perkebunan WALHI Sum-sel,Ketua DPD Sarekat Hijau Indonesia Kota PAlembang
Jika kita lihat isi di dalam PP tersebut, tentunya banyak hal yang patut kita pertanyakan kepada Presiden SBY, atas alasan dikeluarkannya kebijakan kontra produktif itu, yang dihubungkan dengan curat-marutnya sistem pengelolaan dan pengurusan hutan selama ini. Beberapa hal itu diantaranya, Pertama, di tengahnya hancurnya hutan kita, yang selanjutnya telah berkontribusi terhadap berbagai bencana ekologi yang terjadi hampir di seluruh pelosok daerah di negeri ini; Kedua, beragam persoalan sosial yang mengitari kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang hingga saat ini masih terus banyak bermunculan; dan Ketiga, sehubungan dengan keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PBB untuk perubahan iklim pada bulan Desember tahun lalu, dimana pemerintah Indonesia telah berkomitmen akan turut serta mengatasi dampak pemanasan global, yang salah satunya melalui penataan kembali kehidupan hutannya.
Pemerintah harus memperhatikan, penerbitan PP Nomor 2 Tahun 2008, yang membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi pertambangan di dalam kawasan hutan lindung, hanya akan menambah daftar catatan terhadap persoalan kehutanan di Indonesia. Alasan pemanfaatan kawasan hutan, demi mengejar target keuntungan semata, tentunya tidaklah sebanding dengan berbagai persoalan yang akan muncul dikemudian hari, akibat dari proses komersialisasi tersebut. Sangat disayangkan, jika pemerintahan SBY harus rela mengorbankan hutan Indonesia, yang sesungguhnya saat ini telah berada pada situasi yang sangat memprihatinkan. Sia-sia berbagai program dan proyek yang telah dikeluarkan negara, dengan nilai yang tidaklah sedikit untuk memperbaiki nasib hutan Indonesia.
Banyak kalangan mengkhawatirkan, eksploitasi kawasan hutan lindung untuk kegiatan usaha pertambangan, akan sangat membahayakan keselamatan hutan dari sisi konservasi. Kegiatan pertambangan yang dilakukan di luar kawasan hutan selama inipun, secara nyata telah membuktikan berbagai kerusakan lingkungan bagi wilayah sekitar. Dengan penggunaan sistem open fit (terbuka), banyak lubang dan sisa galian yang dihasilkan dari operasi pertambangan, yang semua itu hampir rata-rata selalu dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi. Sebagai contoh di Sumatera Selatan, PT. Barisan Tropical Meaning (BTM), yang beroperasi selama 5 tahun sejak 1997 hingga tahun 2001, di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya MURA, telah berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Paska operasi, lubang-lubang dengan volume kedalaman ratusan meter dan lebar puluhan meter, yang menganga terbuka dibiarkan begitu saja oleh perusahaan.
Pengalihan hutan lindung menjadi aktifitas pertambangan tentunya sangat beresiko. Konversi tersebut akan mengancam berbagai ekosistem kawasan, seperti; tumbuhan dan fauna, serta keasrian udara yang ada di dalamnya. Selain itu, perubahan fungsi kawasan lindung, akan berdampak secara signifikan terhadap pola keseimbangan air dan kesuburan tanah. Dalam hal ini, tentunya masyarakat di sekitar kawasanlah yang paling pertama akan merasakan dampak dari perubahan lingkungan tersebut, selain ancaman lainnya, yaitu semakin terpinggirkannya akses mereka terhadap sumber kehidupannya, memanfaatkan lahan dan hasil hutan.
Jika Presiden SBY beralasan bahwa penerbitan PP Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, hanya diperuntukan bagi 13 perusahaan tambang, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004, kenapa dalam aturan itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Dengan ketidakjelasan tersebut, tentunya akan sangat membuka peluang bagi perusahaan tambang lainnya, untuk turut serta menanamkan investasinya. Selain itu, terdapat kekhawatiran, jika pemerintah memberikan izin terbuka bagi perusahaan pertambangan untuk mengelola kawasan hutan lindung, kemungkinan perusahaan di sektor lainnya, juga akan mencari celah untuk mendapatkan hal yang sama. Selain itu, alasan tujuan pengeluaran PP itu, agar dapat berkontribusi dalam hal pemeliharaan dan rehabilitasi kembali kawasan hutan lindung, tentunya tidaklah akan memadai jika melihat besarnya tarif yang dibebankan terhadap perusahaan. Meski harus disadari oleh SBY, persoalannya tidaklah hanya terbatas pada biaya sewa yang teramat murah, namun terhadap bencana sosial yang bakal dihasilkan dari proses eksploitasi tersebut, adalah kekhatiran utama kita semua.
Dengan laju deforestasi dan degradasi hutan alam yang saat ini telah menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, pemerintah seharusnya lebih menekankan kebijakannya, untuk memulihkan kembali wilayah hutan kritis. Bukanlah sebaliknya, yakni dengan mengelurkan aturan yang bakal membawa kepada resiko akan semakin terababat habisnya hutan tropis kita. Masifnya usaha industri pertambangan di kawasan lindung, hanya akan semakin memperparah kondisi hutan alam Indonesia, yang laju perusakaannya saat ini telah mencapai luasan 2 juta hektar setiap tahunnya, atau setara dengan luas kepulauan Bali (data base Walhi Nasional;2007).
Pengalaman selama ini telah menunjukan, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang hanya mengejar profit semata, telah berkontribusi dalam menghasilkan berbagai bencana struktural. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rentetatan bencana alam, seperti longsor dan banjir adalah potret realitas yang tidak bisa dipungkiri oleh pemerintah.
Karenanya, PP Nomor 2 Tahun 2008 harus dicabut oleh SBY. Selain tidak berfilosofi pada keadilan sosial dan keadilan iklim, Peraturan Pemerintah tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Kehutanan yang terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, Peratutan Pemerintah tersebut juga telah mendistorsi hak dan kewenangan negara sebagimana di jelaskan di dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam UU itu dijelaskan, bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Sementara isi yang dimaksudkan di dalam PP Nomor 2 Tahun 2008, tentang sewa-menyewa, seakan-akan pemerintah memposisikan bahwa Negara adalah pemilik kekayaan hutan kita.